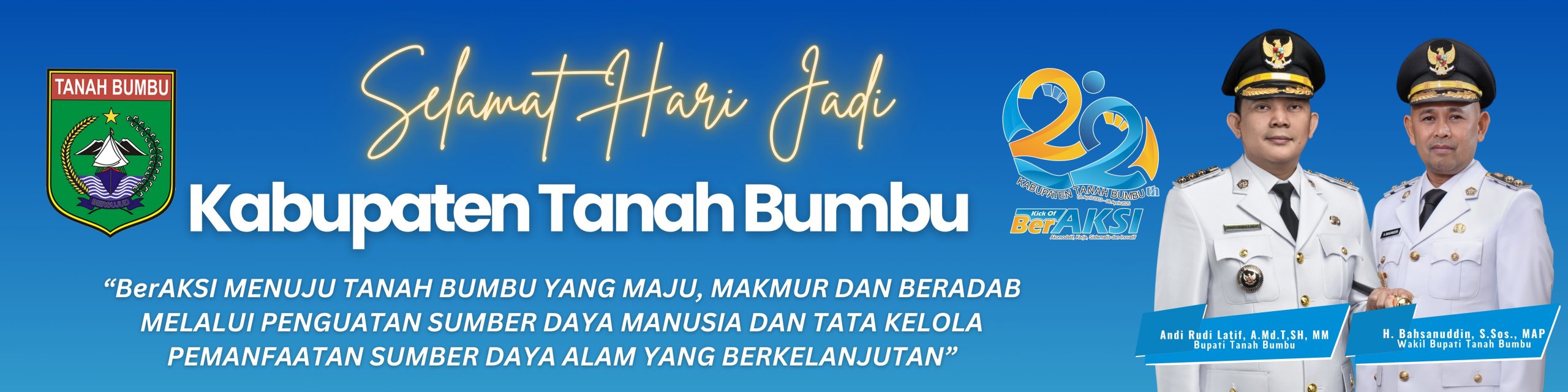Oleh: Ahmad Marjuni: Guru, Aktivis Sosial-Keagamaan, dan pemerhati budaya
Setiap kota memiliki lukanya sendiri. Bagi Banjarmasin, luka itu bernama “Jumat Kelabu”. Sebuah peristiwa kelam yang terjadi pada 23 Mei 1997 silam. Sudah lebih dari dua dekade berlalu, tapi bagi sebagian orang, kenangan itu masih hidup. Menyesakkan, menggetarkan, dan memunculkan tanya bagaimana ini bisa terjadi?
Pagi itu biasa saja, kota masih sibuk seperti biasa. Tapi mendekati waktu salat Jumat, suasana mulai berubah. Sebuah iring-iringan kampanye melewati jalur yang sama dengan para jemaah masjid. Ketegangan mulai terasa. Kata-kata keras dilempar. Emosi memanas. Dan dalam hitungan menit, situasi tak terkendali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Api kerusuhan menyebar cepat. Plaza Mitra terbakar hebat, menewaskan banyak orang yang terjebak di dalamnya. Rumah ibadah dari berbagai agama ikut hangus. Toko-toko dijarah. Jalanan jadi lautan api dan amarah. Hari yang mestinya tenang, penuh berkah, berubah jadi salah satu tragedi sosial terbesar di Kalimantan Selatan.
Di balik kobaran api dan jerit ketakutan, ada pelajaran besar tentang rapuhnya kerukunan, tentang betapa mahalnya damai, dan tentang bagaimana politik bisa berubah menjadi bencana jika tidak diiringi etika dan empati.
Sebagai generasi yang kini tumbuh dalam iklim sosial yang relatif lebih tenang, kita punya kewajiban untuk tidak melupakan. Bukan untuk menabur trauma, tapi untuk menanam kewaspadaan. Kota ini tidak boleh jatuh dua kali dalam lubang yang sama.
Banjarmasin hari ini mungkin lebih ramai, lebih modern, dan lebih berkembang. Tapi apakah jiwanya sudah lebih bijak? Apakah kita sudah benar-benar belajar dari masa lalu? Ataukah luka itu hanya tertutup oleh gedung baru dan lampu kota yang gemerlap?.
Sebagai guru dan pemerhati budaya, saya percaya bahwa peristiwa sejarah seperti ini harus tetap diingat dan dibicarakan terutama di ruang-ruang pendidikan. Anak-anak kita berhak tahu bahwa damai itu ‘tidak turun dari langit,’ tapi dijaga setiap hari lewat sikap dan kebijakan.
Kita bisa mulai dari hal sederhana. Menghormati perbedaan. Menghindari provokasi. Memisahkan tempat ibadah dari agenda politik praktis. Dan yang paling penting adalah menjadikan ruang publik sebagai tempat tumbuh bersama, bukan ajang saling sikut.
Untuk para pemimpin daerah, peringatan 23 Mei harus jadi cermin bahwa suara rakyat bukan hanya soal elektabilitas, tapi juga tentang amanah menjaga harmoni sosial. Jangan biarkan masyarakat kecil jadi korban dari kepentingan besar.
Untuk kita semua, mari pelihara memori bersama ini sebagai titik balik. Agar kita tidak hanya ingat dengan tragedinya, tapi juga dengan semangat untuk bangkit. Dari kelabu menjadi terang. Dari trauma menjadi tangguh.
Karena damai bukan sekadar kondisi, tapi budaya. Dan budaya itu harus terus ditanam, dirawat, dan diwariskan. Jangan sampai Jumat berikutnya menjadi kelabu karena kita lupa untuk saling menjaga.
Mari kita belajar dari jum’at kelabu, bahwa “pembangunan tanpa keadilan, politik tanpa etika, dan agama tanpa empati bisa jadi awal kehancuran.”