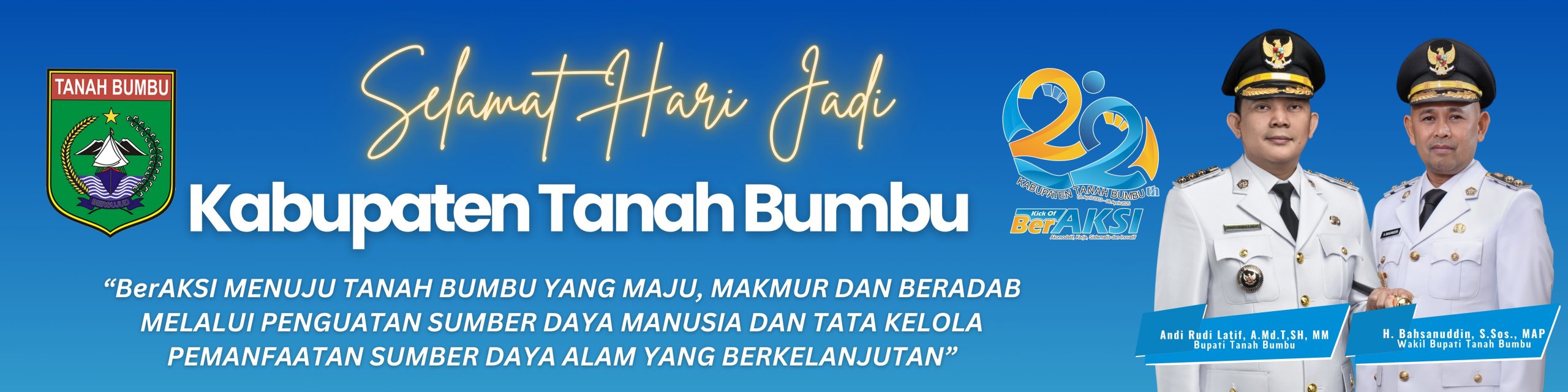Syaipul Adhar, ME: Pegiat Rabithah Melayu Banjar, NU Kultural Kalsel
Pertemuan di Lirboyo kemarin, sejatinya memberi harapan meredanya kisruh di tubuh PBNU antara Rais ‘Aam dan Ketua Tanfidziyah Gus Yahya. Kesepakatan normatif pun lahir, Muktamar Bersama sebagai jalan tengah.
Namun, dibalik kesepakatan itu, ada satu persoalan besar yang justru belum disentuh secara serius. Yakni, perubahan arah organisasi dan pertanggungjawabannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, akar kegaduhan PBNU bukan semata soal prosedur atau ego personal, melainkan kecemasan para kiai terhadap arah jam’iyah yang dianggap bergeser, baik dalam isu keumatan, ideologi global, maupun cara PBNU memaknai keterbukaan. Akhirnya, polemik ini semestinya menjadi momentum muhasabah.
NU tidak kekurangan ulama, tidak kekurangan kader, dan tidak kekurangan sejarah. Yang dibutuhkan adalah kedewasaan berjamaah: taat aturan, ikhlas berkhidmah, dan berani mengelola masa depan—termasuk urusan ekonomi dan SDA—dengan akal sehat dan amanah.
Dalam struktur Nahdlatul Ulama, perlu ditegaskan satu hal mendasar yang kerap dilupakan di tengah polemik: kekuasaan tertinggi jam’iyah NU berada pada Rais ‘Aam, bukan pada figur ketua umum atau pengurus harian.
Rais ‘Aam bukan simbol seremonial, melainkan penjaga garis ideologis, akidah, dan manhaj keulamaan NU. Ia adalah pemegang mandat tertinggi dalam soal arah keagamaan jam’iyah, sementara PBNU bertugas menjalankan roda organisasi sesuai koridor itu.
Dalam hal ini, NU sejatinya sama dengan organisasi keagamaan dunia lainnya. Vatikan, misalnya, terbuka berdialog lintas negara dan agama, tetapi posisi ideologis Gereja Katolik tidak berubah hanya karena pergaulan global. Demikian pula Al-Azhar di Mesir atau Rabithah ‘Alam Islami. Mereka terbuka, namun tegas pada prinsip.
NU seharusnya berdiri di posisi yang sama: inklusif dalam pendekatan, kokoh dalam sikap. Kemerdekaan palestina jangan diutak atik hanya demi cuan sesaat dibalut dialog peradaban.
NU terlalu besar untuk dikelola dengan improvisasi politik sesaat. Ia membutuhkan keteguhan struktur, kepatuhan pada nilai keaswajaan, dan keikhlasan berjuang.
Dalam urusan Palestina, Keadilan global, maupun pengelolaan SDA di dalam negeri, NU harus tampil sebagai organisasi yang terbuka pada dunia, tetapi tidak kehilangan kompas ideologisnya.
Kembali kepada lirboyo agreement, Informasi yang penulis dapat, berkembang menyebutkan satu fakta penting: Rais ‘Aam PBNU sebenarnya mengajak Gus Yahya untuk mundur bersama, mengikuti saran para kiai sepuh sebagai jalan paling elegan dan bermartabat.
Mundur bersama berarti membuka ruang tabayyun jamaah, meredam polarisasi, dan mengembalikan NU ke rel rel muktamirin.
Namun ajakan itu ditolak Gus Yahya. Ia tidak bersedia mundur dan justru mengusulkan opsi Muktamar Bersama.
Padahal Dalam tradisi NU, Rais ‘Aam selalu berada pada posisi yang sangat menjaga adab dan keutuhan jamaah. Beliau sungkan membawa konflik menjadi terbuka dan berlarut, sehingga akhirnya menerima usulan Muktamar Bersama tersebut, meski dengan banyak catatan yang belum dibicarakan secara teknis.
Masalahnya, Muktamar Bersama bukan solusi instan. Ia justru menyimpan banyak pekerjaan rumah yang jika tidak dijelaskan sejak awal, akan melahirkan konflik baru.
Jika sudah begini, Setidaknya ada beberapa poin krusial yang tak boleh diabaikan.
Pertama, soal kepanitiaan.
Siapa panitia Muktamar Bersama? Ini bukan soal teknis kecil. Panitia menentukan legitimasi. Jika panitia dikendalikan satu kubu, Muktamar hanya akan menjadi formalitas kekuasaan, bukan forum koreksi jam’iyah.
Kedua, soal SK-SK PBNU. Selama polemik ini berlangsung, berbagai SK telah dikeluarkan oleh Ketua Tanfidziyah. Bertebaran termasuk ditempat kami kalsel. SK-SK tersebut harus dianulir terlebih dahulu, agar posisi organisasi kembali netral dan tidak timpang menjelang Muktamar Bersama.
Ketiga, Soal otoritas tanda tangan. Dalam masa transisi dan pendinginan konflik, seluruh SK organisasi semestinya ditandatangani bersama oleh Rais ‘Aam dan Sekjen PBNU (Gus Ipul). Ini penting untuk menegaskan bahwa jam’iyah tidak berjalan sepihak dan tetap berada di bawah kepemimpinan kolektif.
Keempat, soal figur netral. Nama Gus Salam, pimpinan MLB, layak dipertimbangkan sebagai Ketua Panitia Muktamar Bersama. Ia berasal dari kalangan muktamirin, relatif netral, dan merepresentasikan aspirasi perubahan ke arah NU yang lebih tertib, beradab, dan setia pada khittah.
Kelima, konsolidasi jamaah. Pasca Lirboyo, konsolidasi akan segera terjadi. Ini bukan konsolidasi perlawanan, melainkan konsolidasi jam’iyah—untuk memastikan Muktamar Bersama tidak melenceng dari tujuan awal: memperbaiki arah organisasi, bukan sekadar mengamankan posisi.
Yang paling penting untuk diingat: Muktamar Bersama bukan tujuan, melainkan alat. Tujuan sejatinya adalah menjawab pertanyaan mendasar umat NU, ke mana arah organisasi ini dibawa, dan siapa yang bertanggung jawab atas perubahan arah tersebut?.
Jika Muktamar Bersama hanya berhenti pada pembagian jabatan dan kompromi elite, maka krisis kepercayaan tidak akan selesai. Tetapi jika ia dijadikan forum jujur untuk evaluasi, pertanggungjawaban, dan koreksi arah, NU justru bisa keluar dari kisruh ini dengan lebih dewasa.
NU sudah terlalu tua dan terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh ego siapa pun. Dalam tradisi ahlussunnah wal jama’ah, menang tidak selalu berarti bertahan, dan mundur tidak selalu berarti kalah.
Kadang, justru di situlah letak kebijaksanaan para kiai sepuh yang hari ini mulai jarang didengar.
Akhirnya, Selamat bermuktamar yang dipercepat. Semakin cepat semakin baik, agar sebelum Ramadan kisruh selesai dan meraih kemenangan dihari yang fitri.